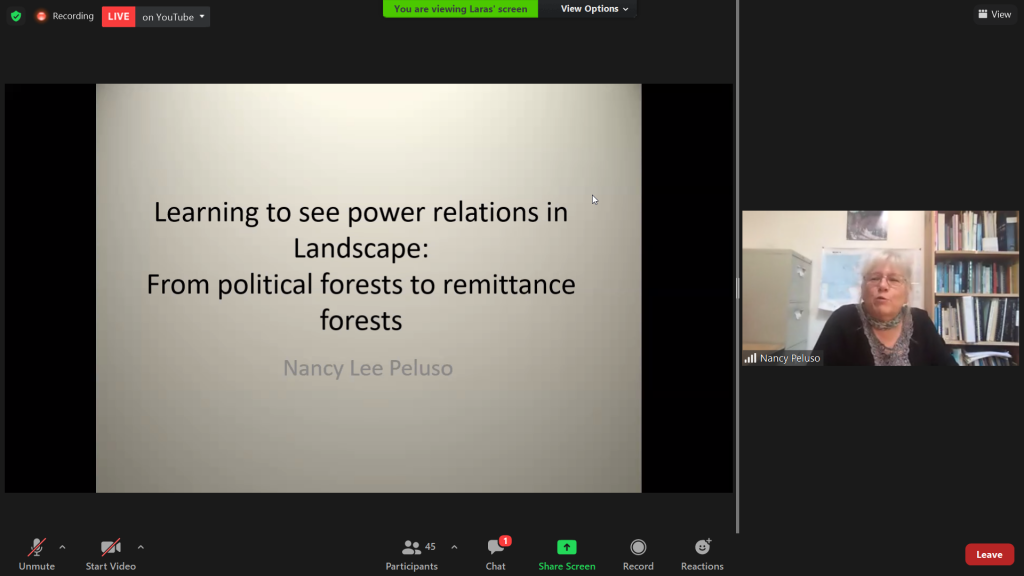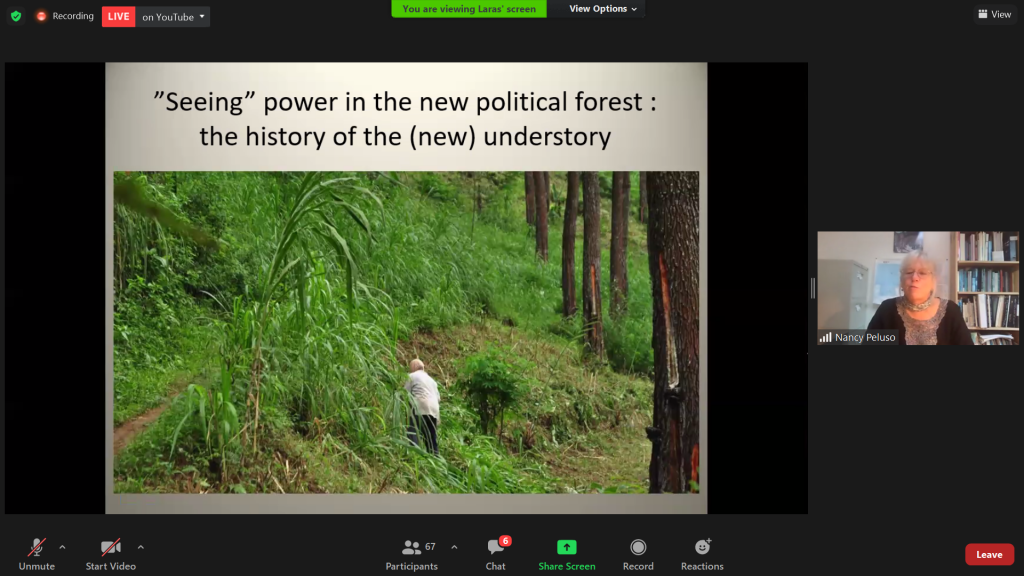(31/05) Prof. Dr. Nancy Lee Peluso dari University of California, Berkeley menjadi pembicara dalam lanjutan acara Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends. Kegiatan kolaborasi Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) ini telah mencapai pertemuan ke-14. Dimoderatori oleh Micah R. Fisher, Ph.D., Prof. Nancy membawakan materi berjudul “Multi-scalar Histories and Political Ecology: Researching Questions of Power, Labor, and Land-based Resources in Indonesia”.
Dalam sesinya, Prof. Nancy pertama-tama membahas mengenai hutan sebagai ruang politik. Hal ini dibenuk oleh praktik-praktik politik, dan dinamikanya merupakan cerminan dari kekuasaan. Sebagai hubungan yang berbentuk konflik dan kolaborasi, kekuasaan dapat “dibaca” dari sebuah lanskap. Mesk begitu, pembacaan penggunaan lahan perlu diiringi dengan adanya pengkonstruksian bagaimana fenomena perubahan lanskap yang terjadi (diistilahkan oleh Prof. Nancy sebagai “trajectory sejarah”), dalam konteks ini merupakan sejarah orang-orang setempat yang penuh dengan tanda-tanda mengenai relasi kuasa tingkat lokal.
Penelisikan sejarah sebagai bagian dari lanskap ini menjadi penting bagi penyelesaian permasalahan lanskap, mengingat pencarian solusi perlu didasari pengetahuan atas asal persoalan (origin of the problem). Oleh sebab itu, hadir konsep ekologi politik (political ecology) sebagai sarana untuk mencari tahu asal konflik melalui sejarah dari berbagai sumber dan level. Dalam ekologi politik, skala spasial dan politik, mulai dari tingkat lokal hingga global, turut ditelisik.
Memasuki bahasan mengenai hutan politik, ada pernyataan menarik dari Prof. Nancy yang menyebut bahwa hutan politik pada dasarnya digunakan untuk mendenaturalisasi hutan. Hutan politik dianggap sebagai sarana kekuasaan teritorial dan mendiferensiasikan hutan dari pertanian. Selain itu, eksistensi hutan politik cenderung mendiskreditkan ruang alami dan masyarakat adat. Tumbuh di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand sejak era kolonial, hutan politik mengukuhkan dan menormalkan kewenangan pemerintah (kolonial dan nasional) atas hutan yang dimiliki dan dikontrol secara monopolistik oleh negara, termasuk kontrol atas tenaga kerja.
Pembahasan mengenai hutan politik ini memiliki perspektif rasional dalam melihat lanskap, spesies, dan tenaga kerja, termasuk mengenai hubungan hutan dan wilayah adat, spesies hutan dan spesies pertanian, serta hubungan kerja di hutan dan lahan jenis lain. Prof. Nancy juga menyebutkan bahwa dalam konteks ini terdapat diskursus “greatest good for the greatest number”. Menarik untuk ditelaah bahwa diskursus ini pada dasarnya juga berkaitan dengan prinsip utilitarianisme (keyakinan bahwa nilai dari suatu hal atau tindakan ditentukan oleh utilitas atau manfaat –KBBI, red.).
Adanya fenomena hutan politik di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana suatu lahan dapat dinyatakan oleh otoritas negara sebagai hutan permanen, dengan batasan yang tetap terlepas dari adanya dinamika tutupan pohon. Lahan-lahan tersebut diatur penggunaannya (dalam bentuk tertulis) berdasarkan tujuan-tujuan politik, diformalkan sebagai “hutan” dan “kawasan hutan” yang sekaligus mendiferensiasikannya dari bentuk-bentuk lahan lainnya. Aturan yang ada juga menempatkan kontrol terhadap semua akses di tangan rimbawan profesional. Prof. Nancy melanjutkan paparannya dengan menjelaskan beberapa dokumentasi lanskap dalam presentasinya dan mengelaborasi hutan politik bersama peserta dalam sesi interaktif.
Membahas lebih mendalam mengenai hutan politik, ketenagakerjaan pada masa-masa awal hutan politik dinilai cenderung bersifat place-based dan gendered. Dalam pekerjaan terkait spesies tanaman pokok/utama (yang relatif lebih formal), laki-laki memegang peranan utama. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan terkait hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang lebih informal, dengan tetap melibatkan laki-laki. Jika dilihat dari sisi jenis pekerjaan, pekerjaan seperti pembersihan, logging, penanaman, pengumpulan, dan transportasi produk seperti resin didominasi laki-laki, sementara perempuan terlibat dalam kegiatan semacam reforestasi dan juga tumpang sari.
Prof. Nancy selanjutnya bercerita mengenai bagaimana di negara-negara Asia Tenggara terdapat keterikatan antara lahan dengan pekerjanya dengan bentuk yang terus berubah sejak zaman kolonial. Era counter-insurgency juga disebut-sebut mengalami dinamika yang diistilahkan sebagai “taking the jungle out of the forest”. Istilah tersebut diinterpretasikan sebagai adanya fenomena pemisahan aspek manusia (termasuk permukiman dan kegiatan subsistensi) keluar dari jungle alias rimba yang liar menuju daerah pertanian.
Dalam penelitian mengenai relasi hutan politik dengan hak adat, Prof. Nancy menyebutkan bahwa ada tiga pertanyaan utama yang terbentuk. Pertama, bentuk dan konten hutan politik saat ini (termasuk aspek wilayah, spesies, dan tenaga kerja). Pertanyaan ini cenderung bersifat present–ish dan place-based. Kedua, bagaimana hutan politik (secara umum) dapat terbentuk. Pertanyaan ini bersifat historis relasional yang dianalisis melalui rekognisi terhadap perubahan besar seperti kebijakan, hukum, perang, dan perpindahan penduduk, serta dijawab secara teoretis atau general. Ketiga, bagaimana hutan politik tertentu memiliki bentuknya saat ini. Pertanyaan ini juga bersifat historis relasional, tetapi tidak bersifat teoretis/general melainkan place-based, kontekstual, dan multiskala. Meski begitu, di lapangan sering kali pertanyaan-pertanyaan tersebut dihadirkan dalam urutan terbalik (yang spesifik lebih dahulu).
Memasuki pembahasan mengenai penelitiannya, Prof. Nancy mengungkapkan pentingnya melihat sejarah hutan politik tidak hanya dari sudut pandang rimbawan yang ada di atas, tetapi juga mencakup masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan sudut pandang atas dan bawah/lokal tidak selalu sama. Prinsip tersebut juga dipegang oleh Prof. Nancy dan tim dalam penelitiannya di hutan pegunungan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di wilayah “Magersari”. Pemilihan wilayah ini tak lepas dari kuatnya kehadiran hutan politik di Jawa.
Dalam paparannya, Prof. Nancy menyebut bahwa eksistensi hutan politik di wilayah tersebut saat ini telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai “hutan remitansi” (remitansi: pengiriman uang dari luar negeri -KBBI, red.). Perbedaan mencolok antara hutan remitansi dengan hutan politik adalah hadirnya peranan mobilitas tenaga kerja dalam pembentukan hutan. Mobilitas ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, tetapi saat ini sudah semakin umum dan jarak mobilitasnya lebih jauh. Fenomena mobilitas ini mentransformasi wujud relasi kekuasaan terkait dengan hutan dan penggunaannya, karena perubahan di hutan saat ini didorong dan dibiayai oleh mobilitas tenaga kerja tersebut, tidak lagi oleh adanya relasi kekuasaan.
Salah satu perubahan yang terjadi adalah pembukaan lahan di bawah tegakan (yang sebelumnya tidak boleh digunakan) sebagai teritori budi daya. Perubahan ini didorong oleh perempuan yang mobile dan bekerja di luar wilayah. Fenomena ini juga mendorong perubahan ekonomi masyarakat Magersari yang saat ini masing-masing telah memiiki rumah, ternak, dan mengalami surplus ekonomi, padahal dahulu dinilai sebagai “warga paling miskin” karena ditinggalkan sebagian besar penduduknya yang bertransmigrasi.
Perkembangan wilayah Magersari ini tak lepas dari berbagai dinamika sejarah yang membentuknya, khususnya berbagai shifting terkait relasi kekuasaan. Beberapa fenomena sejarah yang dimaksud mulai dari peresmian Magersari (medio 1950-an), transmigrasi sebagian besar penduduk Magersaren, perubahan spesies utama hutan dari mahoni ke pinus, perubahan ekonomi, forest violence, hingga kepulangan para migran untuk bekerja di hutan. Salah satu perubahan besar hadir pada medio 2000-an ketika kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi sistem mendorong migrasi transnasional melalui ekspor tenaga kerja yang menimbulkan shifting dalam relasi gender di berbagai bidang, seperti pekerjaan, perjalanan, dan sosial reproduksi. Migrasi tenaga kerja (yang umumnya adalah perempuan) ini juga menghadirkan peluang-peluang baru untuk perubahan karena adanya investasi dari migran yang turut mengubah lanskap, sekaligus shifting relasi kekuasaan dan akses terhadap lahan.
Adanya perubahan ini didorong oleh remitansi (kiriman uang) dari para migran kepada keluarganya di kampung halaman. Dengan harga sapi perah yang lebih terjangkau daripada tanah, masyarakat menggunakan uang kiriman tersebut untuk beternak. Selain memberikan pendapatan subsisten melalui produksi susu harian, sapi yang dibudidayakan juga menjadi tabungan bagi pemiliknya. Kegiatan budi daya tersebut juga tak lepas dari hutan, karena masyarakat terdorong untuk memanfaatkan akses yang dimilikinya terhadap hutan untuk menanam rumput gajah sebagai pakan sapi secara masif. Penanaman rumput gajah di seluruh bawah tegakan hutan ini merupakan bentuk fenomena perubahan di hutan, mengingat sebelumnya budi daya bawah tegakan hutan tak menjadi hal lumrah di komunitas masyarakat tersebut. Jika ditelisik kembali, perubahan ini hadir berasal dari adanya remitansi dari migran. Oleh karena itu, fenomena ini disebut sebagai “hutan remitansi”.
Eksistensi hutan remitansi ini tentu tak lepas dari fenomena migrasi yang juga dibentuk oleh kondisi gendered. Kondisi ini berkaitan dengan pertumbuhan care economy secara global. Care economy adalah suatu sektor ekonomi yang secara spesifik melayani kebutuhan domestik rumah tangga seperti pengasuhan anak dan lansia maupun pekerjaan rumah (termasuk kebersihan dan memasak) yang di Indonesia umumnya diperankan oleh Asisten Rumah Tangga (ART). Dengan adanya ART, seorang perempuan yang telah berkeluarga dapat mengeksploitasi dirinya sendiri (secara sukarela) untuk menjadi penunjang ekonomi keluarga dengan bekerja hingga keluar negeri, didukung oleh keterlibatan negara dalam pelatihan, manajemen, dan ekspor tenaga kerja.
Sementara itu, masyarakat laki-laki yang tinggal di kampung halaman menjadi buruh hutan dengan akses kelola hutan dalam lingkup tertentu. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan adalah menyadap getah/resin dengan bekerja sama bersama rimbawan KPH milik Perhutani. Lalu, kehadiran sumber nafkah baru yaitu usaha budi daya sapi yang dibeli dari remitansi membuat masyarakat buruh hutan tak lagi terlalu berminat menyadap getah. Dinamika ini mendorong perubahan sistem kerja sama KPH dengan warga (karena sistem lama tidak lagi efektif), meski dalam sistem baru berbasis kuota pun sebagian besar masyarakat tak berminat lagi untuk bekerja menyadap getah. Pada akhirnya, sistem lama berbasis perburuhan pun berubah menjadi social forestry. Perubahan ini turut menjadi bagian dari fenomena “hutan remitansi” di wilayah tersebut. Perubahan tersebut juga menghadirkan sistem relasi kekuasaan baru, di mana negara memegang kepemilikan atas teritori dan tegakan pinus, masyarakat mendapat hak guna permukaan dan hasil budi daya bawah tegakan, sedangkan hasil dari getah dibagi antara negara dengan masyarakat.
Meski kehadiran fenomena ini relatif berbeda dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, Prof. Nancy menyebut bahwa pada dasarnya hutan remitansi juga merupakan hutan politik dalam bentuk baru. Hal ini berkaitan dengan adanya peluang dan kemungkinan baru yang terbentuk sebagai bagian dari proses politik. Ada beberapa peluang dan kemungkinan baru yang di-highlight oleh Prof. Nancy, di antaranya adalah penanaman modal dalam bidang peternakan, peran dari akses hutan dalam suplai pakan ternak, perkembangan ekonomi terjadi dengan modal yang relatif kecil, adanya kontribusi bersama dari laki-laki maupun perempuan, dan eksistensi ternak sebagai sumber nafkah lain di samping remitansi dari anggota keluarga yang bekerja di luar wilayah.
Prof. Nancy melanjutkan paparannya dengan membahas metode studinya dalam menemukan hubungan antara fenomena migrasi dengan hutan. Salah satu metode yang cukup menarik adalah pendekatan life histories disertai dengan in-depth interview untuk melihat sejarah turun-temurun di Magersaren tersebut. Pendekatan ini disebut Prof. Nancy sudah relatif jarang digunakan dalam dunia antropologi karena dianggap sebagai pendekatan model lama. Selain itu, studinya juga ditunjang oleh dukungan berbagai pihak dalam kegiatan survei dan pemetaan, serta eratnya hubungan etnografik dengan warga yang dibangun melalui interaksi jangka panjang.
Sebagai penutup, Prof. Nancy menjelaskan mengenai beberapa potensi studi lanjutan, termasuk mendalami fenomena migrasi tenaga kerja dan perubahan akses serta kontrol lahan di dalam dan sekitar perkebunan pada berbagai wilayah. Pertemuan lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang membahas mengenai berbagai fenomena menarik, salah satunya adalah adanya fenomena di wilayah lain mengenai migrasi yang justru berdampak negatif bagi hutan dalam bentuk perambahan hutan. Selain itu, pengaruh fenomena hutan remitansi terhadap relasi gender, termasuk dinamika dalam rumah tangga, juga menjadi bahan diskusi bersama para peserta.
Pertemuan ke-15 Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends akan dilaksanakan pada Kamis, 10 Mei 2021 dengan topik “Intersectionality: Gender and Participation” yang menghadirkan Carol Colfer, Ph.D. sebagai invited speaker. Pertemuan ini dapat disaksikan oleh masyarakat umum melalui live streaming di akun YouTube Forest and Society.