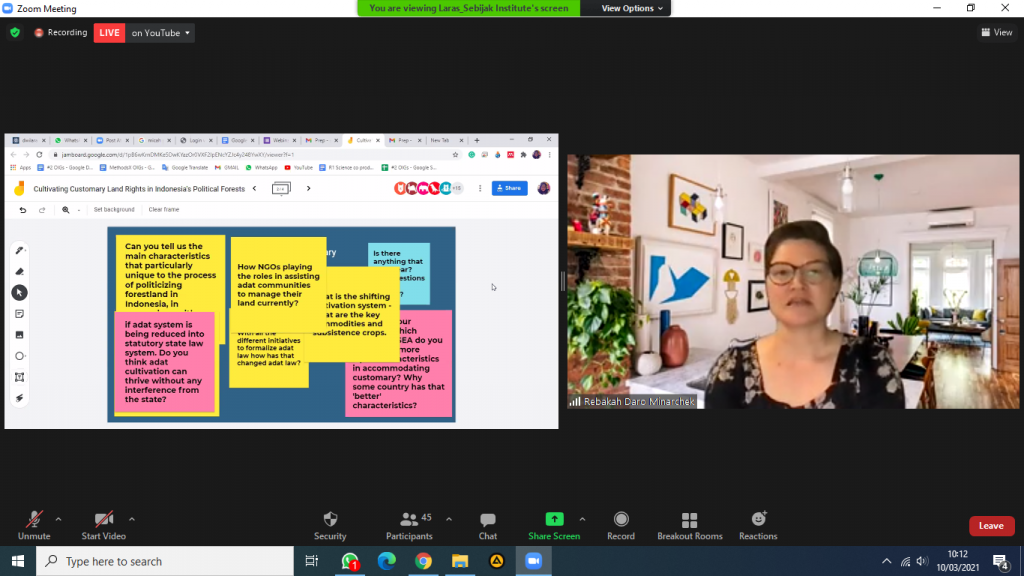(10/03) “The Cultivation of Customary Law in Indonesia’s Political Forests” menjadi tajuk dari Webinar Series yang diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Maret 2021. Webinar ini diselenggarakan oleh Sebijak Institute UGM dan Forest and Society Research Group Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS). Pembicara dalam webinar ini adalah Dr. Rebakah Daro Minarchek, Ph.D, Assistant Teaching Professor di University of Washington Seattle, Amerika Serikat.
Dimoderatori oleh Dr. Micah R. Fisher, webinar dibuka dengan pengenalan mengenai AIFIS oleh Yosef Djakababa selaku Indonesian Country Representative. Memasuki sesi utama, Dr. Rebakah memulai dengan latar belakang studinya di Indonesia sejak tahun 2008 yang memiliki fokus utama dalam hal jejak kebijakan kolonial dalam hukum kehutanan Indonesia. Studi tersebut mendapati bahwa peraturan perundang-undangan yang membingungkan, saling bertentangan, dan korup dalam sistem legal di Indonesia melemahkan hukum dan kekuatannya dalam hal political forest.
Salah satu bagian dari studi Dr. Rebakah adalah studi kasus di Kasepuhan dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang mempelajari pengaruh peraturan terhadap kehidupan anggota masyarakat adat. Studi ini menggunakan unit analisis political forest atas tren historis, aturan konstitusional yang berlaku, dan riset etnografi melalui interaksi langsung dengan masyarakat melalui interview, focus group, dan survei land tenure. Secara umum, studi Dr. Rebakah menilai bahwa aturan-aturan terkait adat yang dianggap menjanjikan nyatanya relatif serupa dengan kebijakan sebelumnya dan tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem legal, bahkan ada yang bertentangan. Akan tetapi, rumitnya problem ini membuat masyarakat lokal cenderung pasif karena sulit diatasi, meski sebenarnya mereka memiliki kesadaran akan hal tersebut. Klaim yang muncul dalam hasil studinya adalah bagaimana penciptaan political forest di Indonesia bisa menghasilkan sistem hukum perundang-undangan yang plural dan dapat menguatkan hukum adat yang dinilai masih relevan dan juga penting bagi masyarakat adat.
Berbeda dari webinar-webinar yang sebelumnya diselenggarakan, dalam webinar ini Dr. Rebakah menonjolkan paparan interaktif dengan peserta melalui platform Google Jamboard. Interaksi ini mendorong paparan berlangsung mengalir demi memfasilitasi diskusi dan pertanyaan dari peserta yang beraneka ragam.
Dr. Rebakah memaparkan bahwa situasi masyarakat adat dan tata hukum agraria turut dibentuk oleh perkembangan sejarah sejak era kolonial, seperti cultuurstelsel dan juga Hukum Agraria 1870 yang mengarah kepada land claim, sementara masyarakat adat tidak memiliki hak dan bukti formal kepemilikan ataupun penggunaan lahan sehingga tersingkirkan. Pasca-kemerdekaan, pengelolaan tata ruang oleh Pemerintah RI masa itu cenderung berfokus kepada peta kolonial dan kurang memfasilitasi masyarakat Halimun Salak yang sebenarnya sudah meminta perubahan peta sejak era kolonial. Faktor-faktor tersebut berimplikasi terhadap kondisi saat ini ketika masyarakat adat hanya memiliki hak penggunaan di Taman Nasional.
Mengenai permasalahan hak atas lahan, dinilai perlu adanya concern tidak hanya sebatas terkait kepemilikan, tetapi juga akses terhadap lahan tersebut dan pemanfaatannya untuk agrikultur, penambangan emas, perburuan, sumber daya air, dll. Hal ini juga berkaitan dengan konflik yang berkutat dalam hal kepemilikan dan penggunaan lahan, juga bagaimana adanya perbedaan akses terhadap lahan karena heterogenitas kelas sosial dan gender. Selain itu, asal usul lahan yang kurang jelas dan tidak adanya dokumen kepemilikan lahan juga menjadi sumber problem.
Pada dasarnya, masyarakat adat di TNGHS mengakui bahwa secara “on paper” wilayah tersebut merupakan Taman Nasional. Di sisi lain, sistem sosial budaya mereka menganggap bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah adat sehingga mereka berhak tinggal di sana. Perbedaan sistem antara institusi pemerintah dan masyarakat ini juga muncul dalam hal pembagian kawasan, di mana pemerintah memiliki sistem kompleks dalam peraturan perundang-undangan (yang juga mencakup Taman Nasional, kawasan lindung, dan kawasan budi daya). Di sisi lain, sistem adat cenderung membagi kawasan dalam tiga bagian, wilayah protektif tertutup, entrusted, dan menyisakan kawasan penggunaan sebagai satu-satunya kawasan yang boleh dimanfaatkan. Kedua sistem kawasan yang tidak berkorelasi ini menimbulkan problem seperti penebangan liar di kawasan lindung yang pada akhirnya berujung kepada hukuman penjara atau denda.
Oleh sebab itu, pemberian ruang dan legitimasi atas hukum adat menjadi penting untuk mengatasi berbagai permasalahan khususnya di kalangan masyarakat adat yang forest-dependent. Akan tetapi, tumbuhnya concern atas urgensi hukum adat ini masih belum diimbangi dengan upaya konkret dalam hal perubahan dan rekognisi hukum adat yang sejajar dengan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, pengaturan dan pengintegrasian hukum adat bisa dikatakan tidak mudah karena dapat melunturkan fleksibilitas dan keunikan khas adat. Dalam hal ini, salah satu benchmark yang dapat digunakan dalam fasilitasi hukum adat adalah Filipina, di mana sistemnya lebih terbuka dan diinterpretasikan dengan lebih luwes. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang masih cukup kaku khususnya terkait ketentuan dokumen legal dan continuous inhabitation.
Dr. Rebakah juga bercerita mengenai bagaimana ia melakukan riset etnografi khususnya yang berkaitan dengan persoalan gender. Dalam proses berbaur dengan masyarakat, melepaskan sudut pandang “wanita Amerika dengan pendidikan Barat” dan menempatkan diri dalam perspektif masyarakat lokal menjadi poin penting. Dengan itu, Dr. Rebakah bisa mendapatkan akses terhadap sudut pandang pria maupun wanita dan mendengarkan bagaimana realita perbedaan akses di masyarakat.
Salah satu bahasan diskusi yang cukup menarik adalah bagaimana hukum adat ini diwariskan kepada generasi muda. Dr. Rebakah menemui bahwa mekanisme pewarisan ini umumnya dilakukan dalam lingkungan keluarga dan pewarisan ini sebenarnya memiliki prospek positif bagi perkembangan hukum adat di Indonesia. Di sisi lain, kecenderungan masyarakat adat untuk mendikotomikan antara insider dan outsider menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat, mengingat faktor edukasi (khususnya outside education) juga menjadi salah satu bagian dari dikotomi. Selain itu, problem finansial dan geografis juga acap kali menjadi penghalang bagi akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi.
Dalam hal keterlibatan pihak eksternal, sebenarnya sudah ada pengakuan pemerintah atas masyarakat adat. Akan tetapi, pengakuan yang sebenarnya mendatangkan berbagai benefit ini nyatanya belum merata karena belum semua kelompok masyarakat adat terakomodasi. Selain itu, berbagai lembaga nonpemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) juga sudah banyak terlibat dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk memfasilitasi persoalan gender dan struktur kekuasaan. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi masyarakat tidak ingin bekerja sama dengan NGO dan ada kemungkinan bahwa NGO terkait memiliki misi tersendiri. Ditambah lagi, persoalan adat ini juga selalu berkutat dengan stigma dari pihak luar, di mana pihak luar menganggap suatu hal sebagai permasalahan, sedangkan di internal masyarakat sendiri tidak merasakan hal tersebut.
Usai paparan, Dr. Rebakah mengutarakan harapannya untuk kembali datang ke Indonesia dan melakukan penelitian kembali. Akan tetapi, pandemi memang menghambat hal tersebut sehingga saat ini ia masih berfokus melakukan riset di Seattle. Selain itu, Dr. Rebakah juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan dan juga antusiasme peserta yang besar sehingga diskusi berjalan interaktif dengan berbagai pertanyaan menarik. Di sisi lain, paparan Dr. Rebakah juga sangat insightful bagi para peserta, khususnya dalam hal political forest dan hukum adat di Indonesia yang hingga saat ini masih belum benar-benar direkognisi.