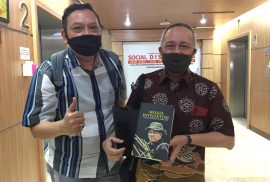(8/10) Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan (Sebijak Institute) Fakultas Kehutanan UGM melaksanakan kegiatan Talkshow dalam rangkaian kegiatan Dies Natalies Fakultas Kehutanan UGM yang ke-57. Kegiatan talkshow ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 8 Oktober 2020 dengan judul tema “Politik Perdagangan Internasional: Pangan, Pasar dan Hutan?”.
Kegiatan talkshow ini dibuka oleh sambutan dari Wakil Bidang Kerjasama dan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Dr. rer. Silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut.,


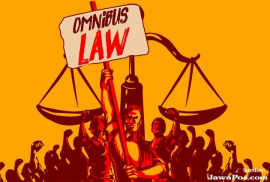

 Irfan Bakhtiar, S.Hut., M.Si. (Director of SPOS Indonesia Program, Yayasan Kehati)
Irfan Bakhtiar, S.Hut., M.Si. (Director of SPOS Indonesia Program, Yayasan Kehati) Kamis, 8 Oktober 2020
Kamis, 8 Oktober 2020 Pukul: 09.00-11.00 WIB
Pukul: 09.00-11.00 WIB Zoom
Zoom